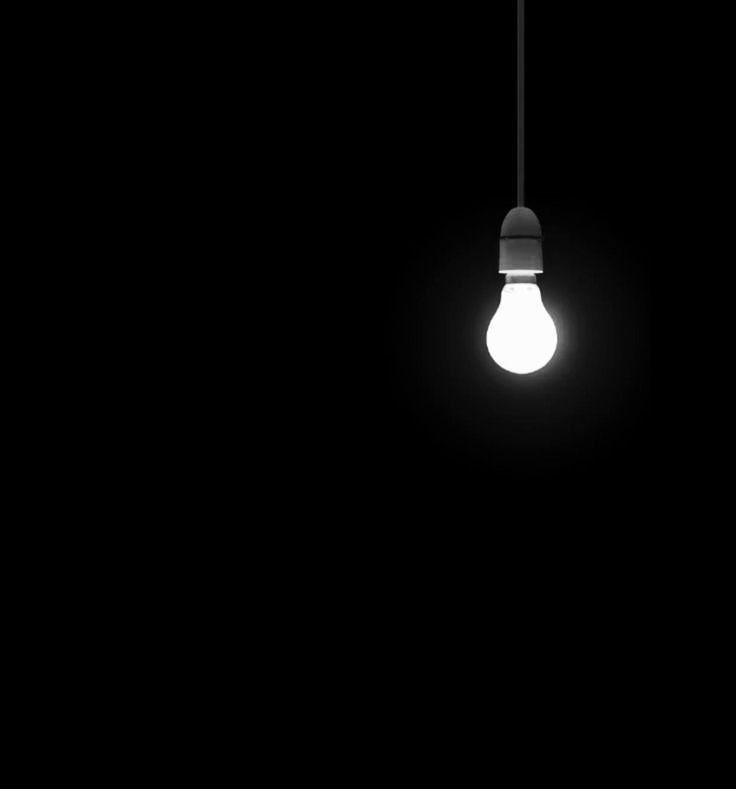Harapan di Balik Sorban

Di sebuah pesantren kecil di lereng gunung Wilis. Seorang santri duduk bersila di bawah pohon beringin tua. 17 Agustus, bendera merah putih berkibar di halaman pesantren, diiringi lantuna lagu kebangsaan dari para santri yang bersura serak tapi penuh semnagat.
Fikri bukan santri biasa, ia adalah anak dari petani miskin yang sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Baginya, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan tetapi bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Ia percaya bahwa ilmu adalah jalan menuju kemerdekaan sejati.
Setelah upacara. Kyai Ma’ruf memanggil Fikri ke serambi masjid.
“Fikri” ujar sang kyai.
“Apa arti kemerdekaan bagimu?”
Fikri menunduk sejenak, lalu menjawab “Kemerdekaan adalah saat seorang anak desa bisa bermimpi besar tanpa takut dihina. Saat santri bisa berbicara tentang teknologi, ekonomi, bahkan masa depan bangsa tanpa dianggap hanya tahu kitab kuning.”
Kyai Ma’ruf tersenyum. “Itu harapan yang mulia, tapi harapan harus dibarengi dengan perjuangan. Apa yang akan kau lakukan?”
Fikri menggenggam sorban putihnya, “Saya ingin mendirikan sekolah gratis di desa saya kyai. Tempa anak-anak bisa belajar agama dan ilmu dunia. Tempat harapan tumbuh bukan hanya doa yang dipnjatkan.”
***
Hari-hari berlalu, Fikri lulus dari pesantren, melanjutkan kuliah dengan beasiswa, dan bertahun-tahun kemudian Kembali ke desanya. Ia mendirikan sebuah Madrasah kecil bernama Harapan Bangsa. Di sana, anak-anak belajar membaca Al-Qur’an dan juga merakit computer dari barang bekas.
Setiap 17 Agustus, Fikri mengibarkan bendera di halaman Madrasah. Diiringi dengan suara anak-anak menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dengan logat jawa yang kental. Dimana itulah kemerdekaan! Saat harapan tumbuh di tanah yang dulu hanya tahu pasrah.
Tahun-tahun berlalu, dan Madrasah Harapan Bangsa mulai dikenal. Bukan karena bangunannya yang megah—justru sebaliknya. Bangunannya masih berdinding bambu dan beratap seng. Tapi semangat para santri dan muridnya memancar seperti cahaya fajar.
Fikri tak hanya mengajar, ia juga turun kesawah untuk membantu orang tua murid yang kesulitan ekonomi. Ia percaya pendidikan tak bisa tumbuh di tanah yan lapar. Maka ia mengajarkan pertanian organik, mengajak warga menanam sayur di pekarangan, serta membuat koprasi kecil untuk menjual hassil panen.
Namun,harapa tak selalu berjalan mulus.
Suatu hari, seorang pejabat dari kota datang. Ia menawarkan bantuan dan tapi dengan syarat: “madrasah harus kembali mengikuti kurikulum yang disesuaikan” dan fikri diminta untuk berhenti mengajarkan materi tentang keadilan sosial dan hak rakyat kecil.
“Kau, terlalu idealis Fikri!” Kata pejabat itu.
“Anak-anak desa, mereka harus tahu. Karena do’a tanpa kesadaran akan hak, hanya akan jadi bisikan yang tak pernah didengar.”
Pejabat itu pergi, dan bantuan pun batal. Madrasah kembali harus bertahan dengan hasil sumbangan warga dan hasil kebun tapi semangat tak padam.
Suatu malam, Fikri duduk di serambi madrasah. Menatap langit yang bertabur Bintang. Di sampingnya seorang santri kecil bernama Zidan bertanya
“Ustadz, kenapa kita tetap belajar meski tak punya listrik dan buku bagus?”
Fikri tersenyum,
“Karena harapan tak butuh lampu Zidan. Ia cukup dengan keyakinan dan kerja keras.”
Zidan kelak menjadi santri pertama yang diterima di Universitas Negri. Ia menulis esai tentang “Perjuangan Santri Desa” dan esainya viral. Wartawan kemudian datang serta pemerintah mulai melirik dan bantuan pun mengalir tanpa syarat.
Madrasah Harapan Bangsa kini berdiri kokoh. Tapi sorban putih tetap sama lusuh. Penuh tembelan. Tapi menjadi simbol perjuangan. Ia tak pernah ingi jadi tokoh besar. Ia hanya ingin menjadi jembatan kecil antara harapan dan kenyataan.
Setiap 17 Agustus, ia berdiri di depan murid-muridnya dan mengulang 1 kalimat.
“kemerdekaan bukan hadiah. Ia adalah warisan yang harus dijaga dengan ilmu, iman dan keberanian.”
Dan sanubari para santri, harapan yuntuk Indonesia terus tumbuh dari desa kecil. Dari pesantren sederhana, dari sorban yang tak pernah lepasn dari kepala seorang guru bernama Fikri.
***
Tahun 2030, desa tempat Madrasah Harapan Bangsa berdiri dengan membawa wajah baru. Jalan—Tanah menjadi aspal, sinyal internet menjangkau, dan anak-anak desa tak lagi malu menyebut cita-cita mereka. Seperti manjadi ilmuan, dokter, pemimpin negri.
Namun perubahan membawwa tantangan baru. Beberapa orang tua mulai khawatir bahwa anak-anak sekarang terlalu sibuk dengan teknologi. Keluh salah seorang petani tua bernama pak Raji. Mereka lupa ngaji, lupa adab.
Fikri mendengar keluhan itu denga hati terbuka. Ia tahu, bahwa kemajuan tak boleh menghapus akar. Maka ia mengadakan program baru yakni ngaji digital. Santri belajar tafsir dan fikih melalui tablet; tetapi mereka tetap duduk di majlis, besorban, serta tatap beradab.
Ditengah itu, datang kabar mengehutkan. Fikri diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai “Tokoh Pendidikan Inspiratif” ia pun ragu.
“Saya bukan siapa-siapa.” Ujarnya kepada Kyai Ma’ruf yang sudah mulai sepuh.
Kyai Ma’ruf tersenyum lemas. “Justru karena kau merasa bukan siapa-siapa, kau layak jadi teladan. Pergilah bawa suara desa ke kota.”
Di Jakarta. Fikri berdiri di panggung besar. Di depannya terdapat pejabat, akademisi dan tokoh nasional. Dikala itu ia tetap menggunakan sorban yang sama, dan ketka diminta berpidato ia berkata:
“Saya bukan lulusan luar negri, saya hanya santri dari lereng gunung. Tapi saya percaya, Indonesia akan besar bukan karena gedung tinggi atau teknologi canggih. Tapi karena hati yang bersigh dan tekad yang tak gentar. Kemerdekaan bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah janji bahwa anak desa bisa bermimpi. Dan mimipi itu tak akan ditertawakan.”
Pidato itu viral. Banyak yang terinspirasi olehnya, tetapi Fikri tetap kembali kemadrasahnya. Menolak tawaran jabatan dan popularitas. Ia memilih tetap menjadi guru, bersorban serta tetap menyiram harapan dari tanah yang sederhana.
Dan setiap tahun, ketiak bendera Merah Putih berkibar di halaman madrasah. Suara anak-anak menyanyikan “Indonesia Raya” tak lagi serak. Ia penuh semangat, harapan dan cinta pada negri yang mereka yakini bisa lebih adil, cerdas serta lebih beradab.
Diantara sorban yang lusuh dan papan tulis yan mulai pudar. Harapan untuk Indonesia terus tumbuh melalui desa kecil dari pesantren sederhana, dari seorang santri yang percaya bahwa kemerdekaan sejati adalah saat ilmu dan iman berjalan beriringan.
Oleh: Rachael Al-Farabys